Kembar buncing merupakan suatu istilah yang merujuk pada keadaan kembar berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Di Bali, kembar buncing adalah kasus yang khusus, spesial. Dapat dikatakan demikian karena kembar buncing dianggap sebagai sebuah anomali, penyimpangan yang tidak biasa. Sebagaimana digambarkan oleh budayawan Ketut Sumarta dan tokoh masyarakat adat Buleleng yang juga adalah Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Buleleng, Made Rimbawa, di dalam artikel koran Kompas tanggal 30 April 2004, Bali di bawah kerajaan di masa silam menghembuskan dua pandangan berbeda tentang kembar buncing.
Jika kembar buncing terlahir dari pasangan suami istri di lingkungan keluarga kerajaan maka pasangan bayi disambut sebagai berkah yang diyakini akan mendatangkan keberuntungan di kemudian hari. Kehadiran pasangan bayi disambut dengan penuh kehormatan melalui upacara khusus. Selanjutnya, sang bayi dipelihara dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang pula. Namun, pemeliharaannya dilakukan secara terpisah hingga mencapai usia dewasa. Di waktu lampau itu, bayi buncing di lingkungan kerajaan dibesarkan secara terpisah. Setelah mencapai dewasa, keduanya dipertemukan kembali dan dikawinkan sebagai suami istri. Dibandingkan dengan anak lainnya, anak kembar buncing ini dianggap memiliki tempat yang sangat terhormat di lingkungan kerajaan.
Namun, sebaliknya, bila bayi serupa terlahir dari keluarga biasa di luar lingkungan kerajaan, sang raja melihatnya dengan anggapan berbeda. Sang raja menegaskan kepada masyarakatnya bahwa kembar buncing dari pasangan suami istri masyarakat biasa adalah aib. Karenanya harus dikucilkan selama tenggang waktu tertentu. Pengucilan itu sendiri bermaksud membersihkan aib bawaan kembar buncing. Sumarta dan Made Rimbawa yang merujuk dari dokumen sastra tua menggambarkan, anggapan noda aib dari kembar buncing bersumber dari ajaran raja yang menjelaskan bahwa pasangan kembar tersebut ketika dalam kandungan telah melakukan hubungan seksual.
Sanksi pengucilan atas bayi kembar buncing adalah warisan budaya lama dari leluhur raja yang diyakini menurunkan ajaran bahwa pasangan kembar buncing dari kalangan biasa adalah aib. Perlakuan atau pandangan diskriminatif dari raja ini berubah menjadi mitos yang selanjutnya tertuang dalam awig-awig atau peraturan adat. Di Bali, setiap desa pakraman (desa adat) memiliki awig-awig yang diturunkan sejak leluhurnya. Tidak jarang awig-awig desa yang satu berbeda dengan desa adat lainnya. Desa pakraman sendiri adalah lembaga yang memiliki otoritas penuh secara otonom atas lingkungan komunitas adatnya. Namun, dalam perjalanannya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan jaman yang semakin modern, banyak yang telah menyadari awig-awig seperti itu tidak layak lagi dijunjung. Alasannya karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan nurani kemanusiaan, hukum agama dan hukum lainnya.
Pimpinan adat bersama pimpinan agama dan jajaran pemerintah di Bali juga melihat bahwa tidak sedikit dari awig-awig itu yang sepantasnya direvisi karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan zamannya. Tersebutlah sebuah payung hukum berupa kesepakatan dan peraturan daerah sejak tahun 1951. Menyusul, Bhisama PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) tahun 1971 dan Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2002. Semuanya berintikan mengimbau kepada komunitas adat, terutama jajaran prajuru (pengurus desa adat), supaya menyesuaikan awig-awig-nya dengan hukum agama dan hukum yang berlaku.





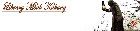






0 komentar:
Posting Komentar